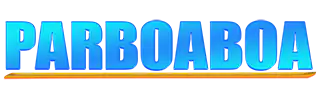PARBOABOA, Jakarta - Pengesahan revisi Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada Kamis (20/03/2025) menuai kritik tajam.
Proses yang terburu-buru, minim partisipasi publik, serta berlangsung secara tertutup menimbulkan kekhawatiran terhadap arah demokrasi di Indonesia.
Terlebih, pertemuan Komisi I DPR RI dengan pemerintah pada Sabtu (15/03/2025), di sebuah hotel bintang lima di Jakarta dianggap bertolak belakang dengan semangat efisiensi anggaran pemerintahan Prabowo.
Asosiasi LBH APIK Indonesia bersama 18 kantor LBH APIK di berbagai daerah dengan tegas menolak revisi UU TNI.
Mereka menilai, perubahan aturan ini berpotensi melemahkan supremasi sipil dan menghidupkan kembali dwifungsi militer.
"Rencana perluasan peran TNI ke sektor politik, ekonomi, bisnis, pembangunan, dan keamanan dikhawatirkan membuka jalan bagi dominasi militer dalam pemerintahan," tulis mereka dalam pernyataan yang diterima PARBOABOA, Rabu (19/03/2025).
"Jika militer semakin aktif di ranah sipil, batas antara otoritas sipil dan militer akan semakin kabur, mengancam sistem pengawasan dan kontrol terhadap institusi militer," lanjut mereka.
Sebelumnya, Indonesia telah berupaya menghapus dwifungsi ABRI/TNI sejak reformasi 1998 agar militer kembali ke tugas utama sebagai penjaga pertahanan negara, bukan sebagai pengambil kebijakan sipil.
"Namun, revisi ini justru berpotensi membawa Indonesia kembali ke era otoritarianisme, membuka celah bagi penyalahgunaan kekuasaan, dan mengancam prinsip demokrasi," ujar mereka.
Selain itu, LBH APIK juga menyoroti dampak revisi UU TNI terhadap kehidupan perempuan dan komitmen Indonesia terhadap Pengarusutamaan Gender (PUG). Beberapa risiko yang dapat muncul, antara lain:
Pertama, Meningkatnya Impunitas dalam Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP). Menurut asosiasi, Revisi UU TNI memungkinkan perwira aktif menduduki posisi strategis di Mahkamah Agung dan lembaga peradilan lainnya.
"Hal ini berisiko melemahkan supremasi sipil dalam sistem peradilan serta mengancam independensi kekuasaan yudikatif sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945," kata mereka.
LBH APIK mencatat banyak kasus KtP yang melibatkan anggota TNI cenderung disidangkan di peradilan militer, yang belum sepenuhnya menerapkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) 3/2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
"Akibatnya, banyak korban yang tidak mendapatkan keadilan, sementara pelaku menikmati impunitas."
Kedua, Legitimasi Militer dalam Proyek Pembangunan Berisiko Kriminalisasi Perempuan Pembela HAM. Peran militer dalam proyek pembangunan berpotensi meningkatkan kriminalisasi dan kekerasan terhadap Perempuan Pembela HAM (PPHAM).
"Sepanjang era reformasi, keterlibatan militer dalam konflik agraria telah memperburuk situasi perempuan yang berjuang mempertahankan ruang hidupnya," jelas mereka.
Banyak kasus perampasan tanah yang berujung pada represi terhadap perempuan dan komunitas adat, termasuk kekerasan seksual.
Ketiga, Mempersempit Akses Perempuan terhadap Jabatan Sipil Strategis. Saat ini, lebih dari 2.100 anggota aktif TNI telah menduduki posisi strategis di sektor sipil.
"Jika revisi UU TNI disahkan, jumlah ini diperkirakan akan bertambah, sehingga memperkecil peluang perempuan dalam mengisi posisi kepemimpinan di berbagai sektor."
Kultur militer yang hierarkis dan maskulin juga dinilai kurang sensitif terhadap isu kesetaraan gender, sehingga dapat menghambat representasi perempuan dalam pengambilan keputusan.
Keempat, Penguatan Pendekatan Militeristik yang Patriarkis. Meningkatnya peran militer dalam pemerintahan berisiko menekan gerakan perempuan dan membatasi ruang ekspresi kelompok yang kritis terhadap kebijakan negara.
Situasi ini bisa menyeret kembali Indonesia ke masa Orde Baru, di mana peran perempuan lebih diarahkan ke ranah domestik, sementara partisipasi mereka dalam politik dan kepemimpinan dibatasi.
Kelima, Ancaman terhadap Kebebasan Berekspresi. Revisi UU TNI juga mencakup perluasan kewenangan TNI dalam bidang keamanan siber dan operasi militer non-perang.
Tanpa pengawasan sipil yang memadai, kebijakan ini berisiko digunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi, terutama bagi perempuan dan masyarakat sipil yang mengkritisi kebijakan pemerintah.
"Jika dibiarkan, hal ini dapat mempersempit ruang demokrasi dan meningkatkan represi terhadap aktivis perempuan, sebagaimana yang terjadi di masa lalu," ungkap mereka.
Sorotan Amnesty
Terpisah, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengkritik sejumlah pasal kontroversial dalam draft revisi UU TNI.
"Kami melihat UU TNI masih memuat pasal-pasal bermasalah yang berpotensi mengancam demokrasi, supremasi hukum, dan hak asasi manusia," ungkapnya pada Jumat (21/3/2025).
Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa aturan ini masih membuka peluang bagi militer untuk terlibat dalam urusan non-pertahanan dan menempati jabatan sipil, yang dapat melemahkan kontrol sipil terhadap TNI.
Meski demikian, Usman mengakui bahwa beberapa usulan Amnesty International telah diakomodasi dalam draf akhir UU TNI.
Beberapa perubahan yang telah disetujui, antara lain penghapusan Pasal 7 terkait narkotika, serta revisi Pasal 8 yang awalnya mengatur tentang keamanan wilayah di darat menjadi pertahanan wilayah di darat.
Selain itu, usulan untuk menghapus ketentuan yang memungkinkan prajurit TNI aktif menempati posisi di Kementerian Kelautan dan Perikanan telah diterima.
Namun, terkait Kejaksaan Agung RI, kompromi dilakukan dengan menempatkan prajurit TNI di posisi Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer.
Kendati ada perubahan tersebut, Usman tetap menegaskan bahwa idealnya tidak ada satu pun kementerian atau lembaga sipil yang dapat diisi oleh prajurit TNI aktif.
Hal ini merujuk pada TAP MPR Nomor VII Tahun 2000 yang secara jelas tidak memberikan ruang bagi pengecualian dalam hal ini.
"Dari perspektif Amnesty International, kami tetap berpegang pada TAP MPR Nomor VII Tahun 2000 yang memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan UU TNI. Seharusnya aturan ini menjadi acuan utama dalam penempatan prajurit TNI di lembaga sipil," tegasnya.
Usman juga mempertanyakan urgensi revisi UU TNI yang dianggapnya tidak memberikan dampak signifikan terhadap transformasi TNI menjadi lebih profesional. Sebaliknya, ia menilai revisi ini justru dapat melemahkan profesionalisme militer.
Sebagai alat pertahanan negara, TNI seharusnya difokuskan pada tugas utama mereka dan bukan terlibat dalam jabatan sipil atau program non-pertahanan seperti cetak sawah dan ketahanan pangan.
Dalam konteks reformasi sektor keamanan, Usman berpendapat bahwa pemerintah dan DPR seharusnya lebih memprioritaskan revisi UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
Menurutnya, argumen bahwa UU TNI sudah usang memang tidak keliru, namun hal itu juga berlaku bagi UU lainnya seperti UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang masih memiliki relevansi besar terhadap TNI.
Oleh karena itu, ia menekankan bahwa agenda revisi UU Peradilan Militer jauh lebih mendesak dibandingkan perubahan UU TNI.
"Langkah ini merupakan bagian dari kewajiban konstitusional negara dalam menjamin prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) bagi seluruh warga negara, tanpa kecuali. Reformasi peradilan militer sendiri telah diamanatkan oleh TAP MPR No. VII Tahun 2000 dan UU Nomor 34 Tahun 2004," pungkas Usman.